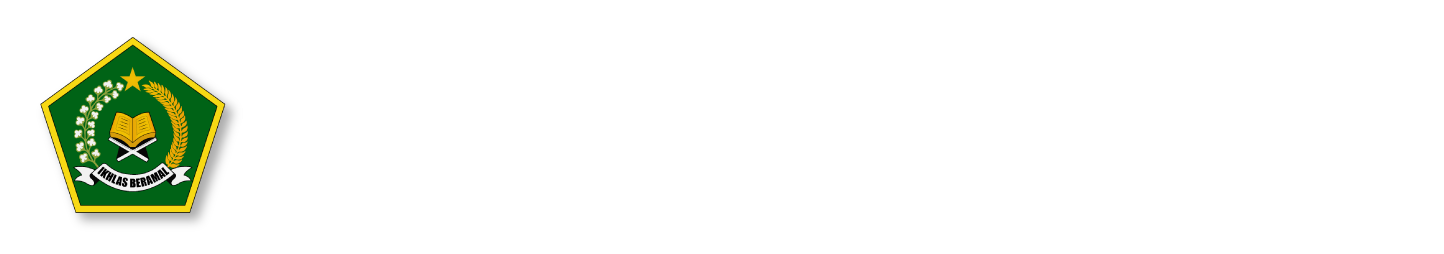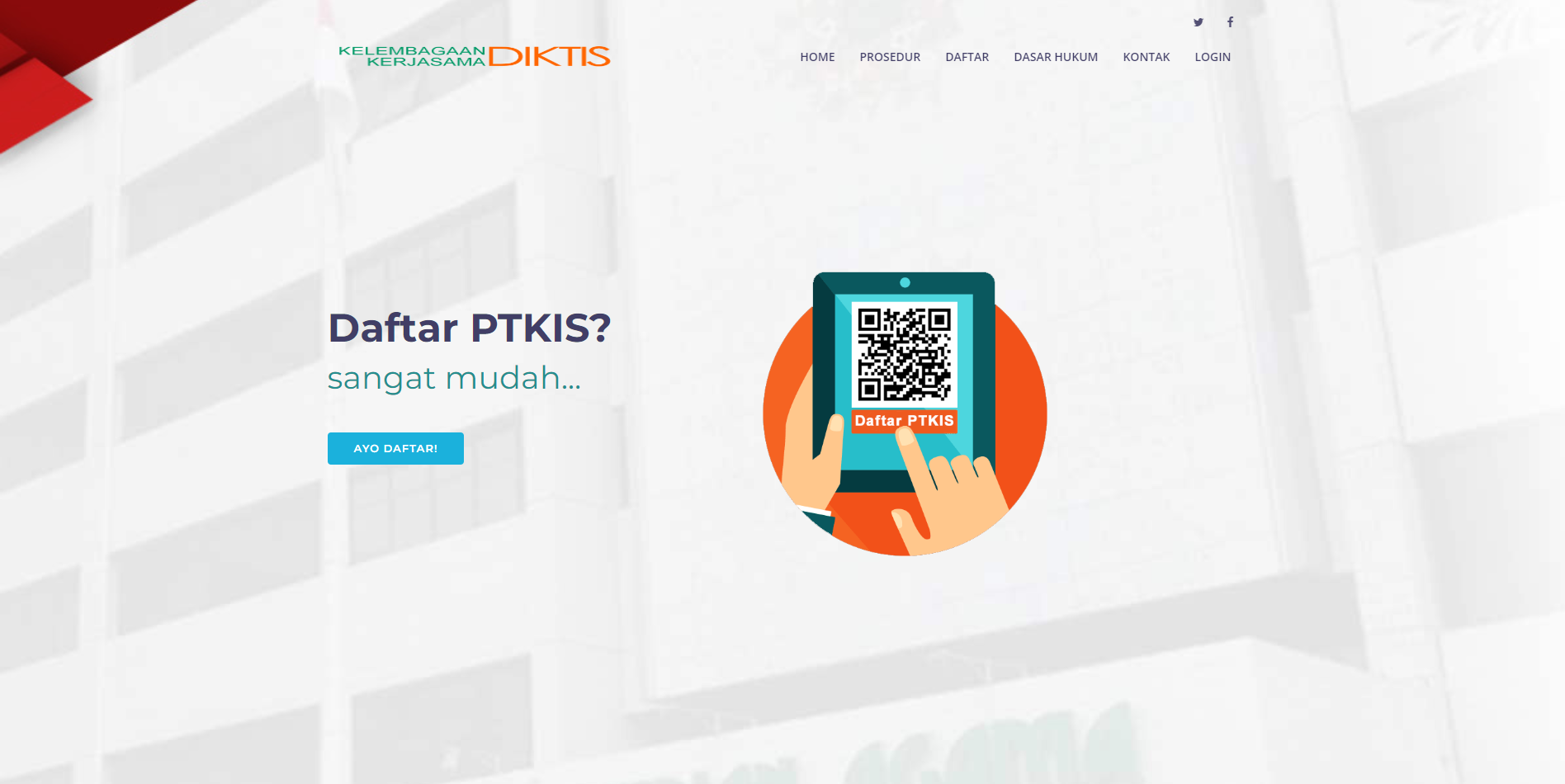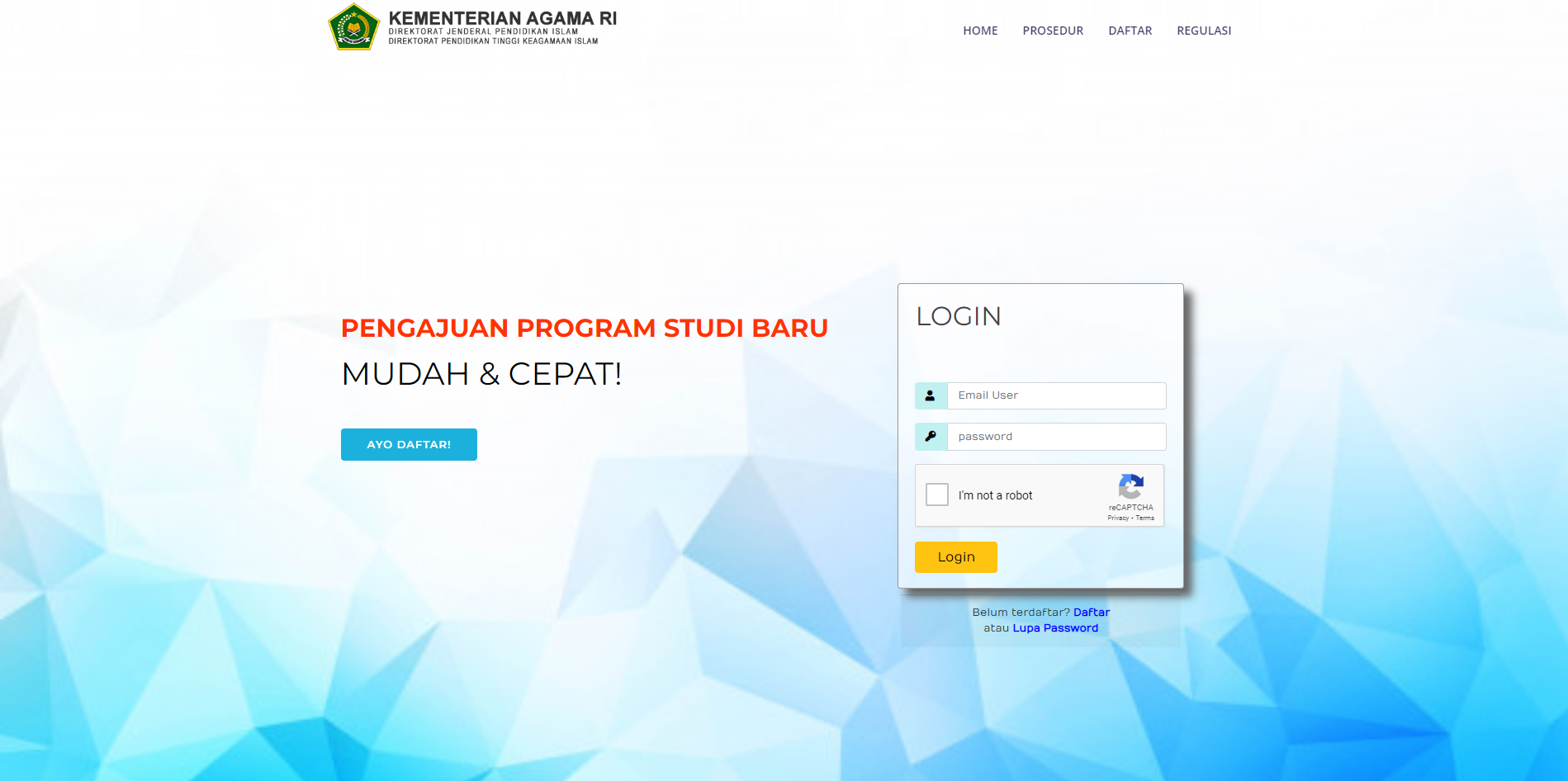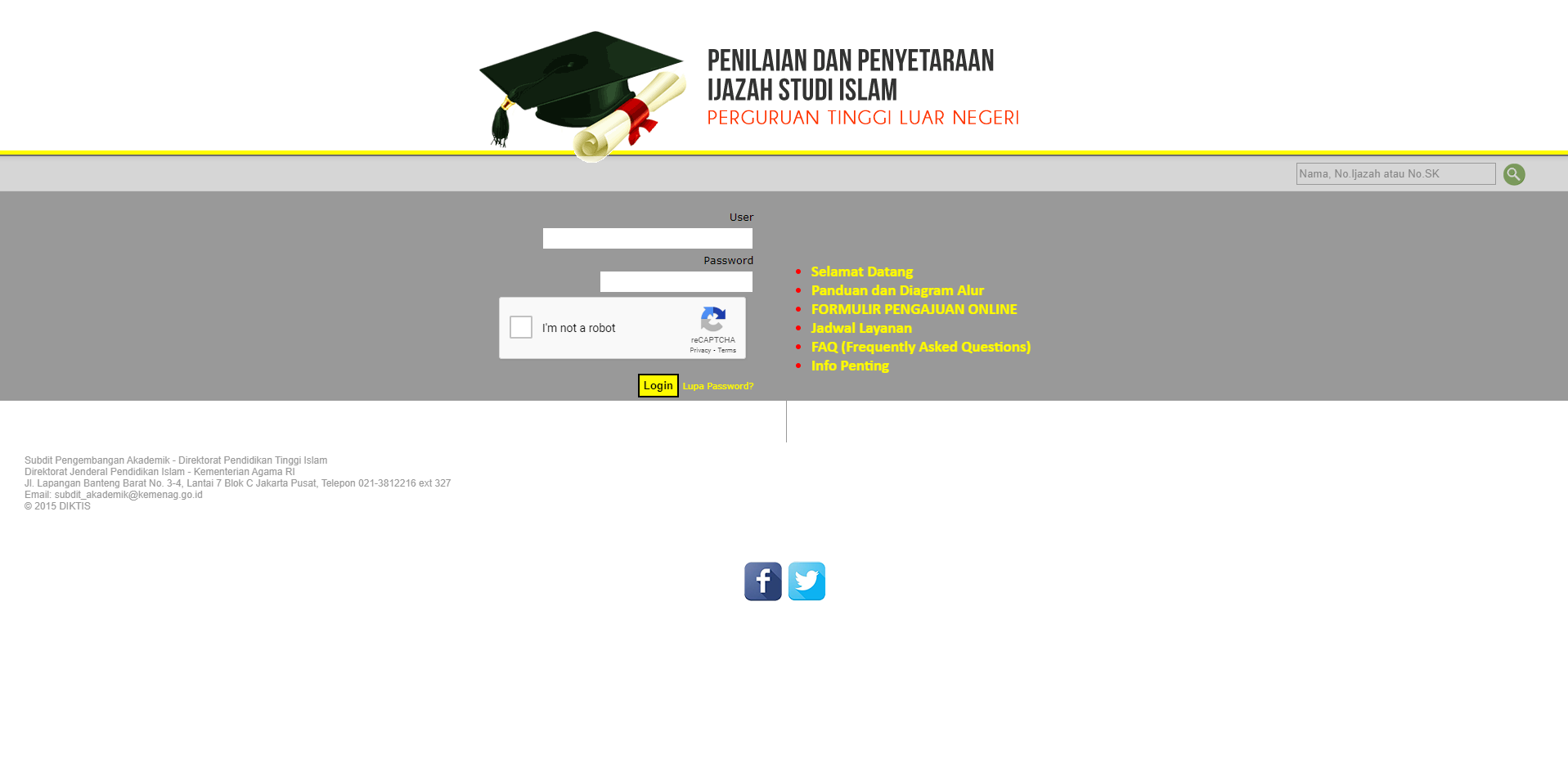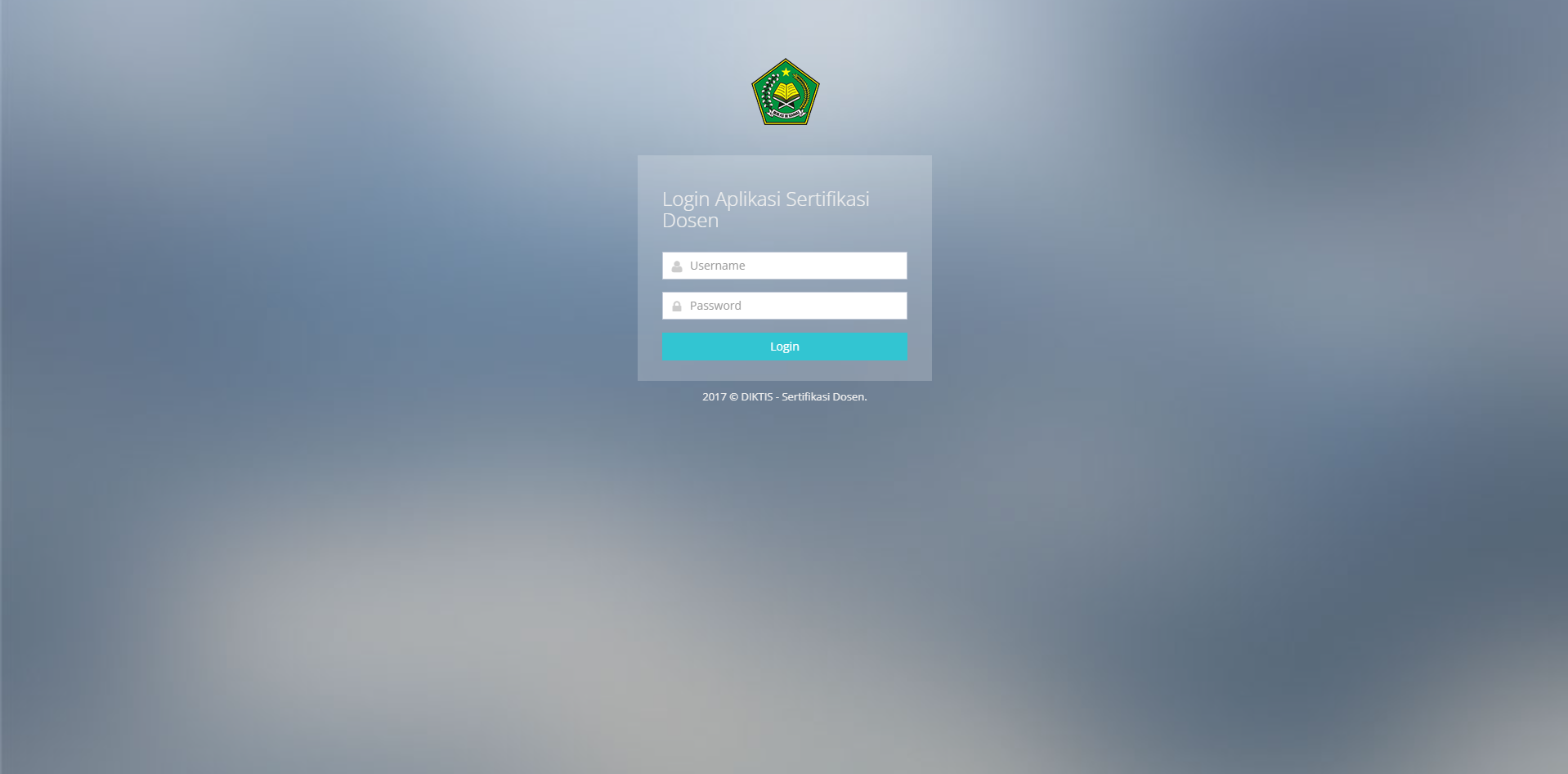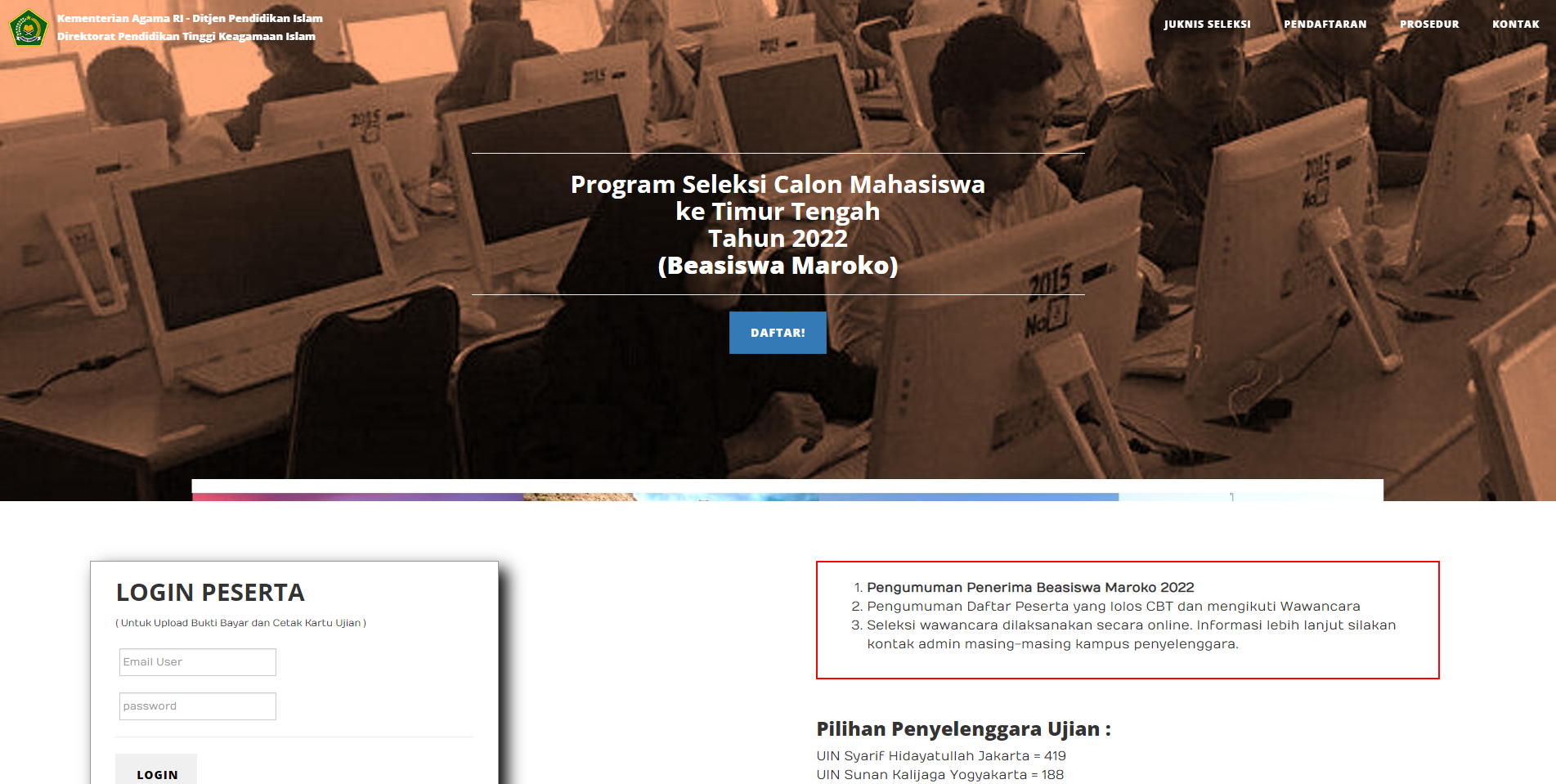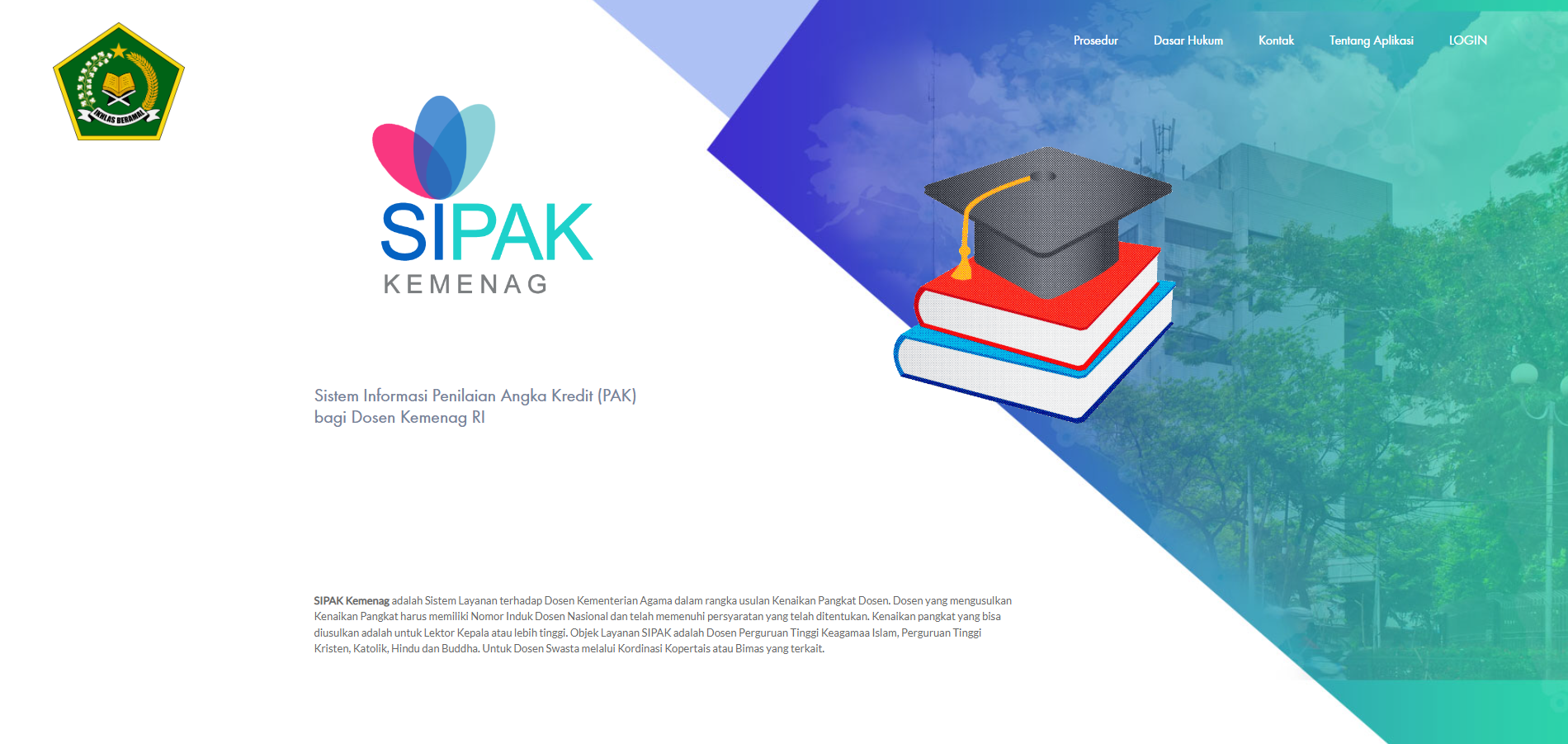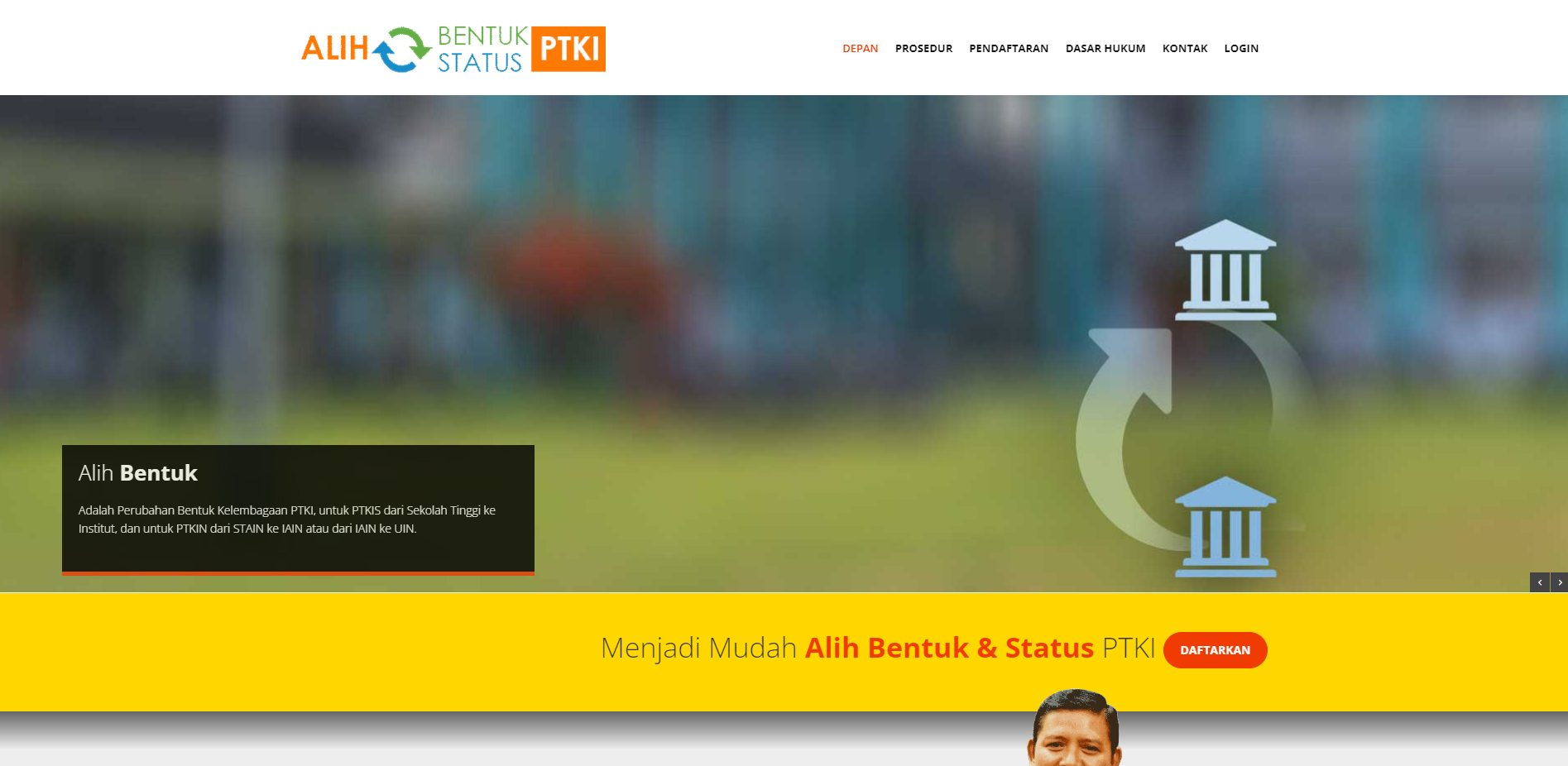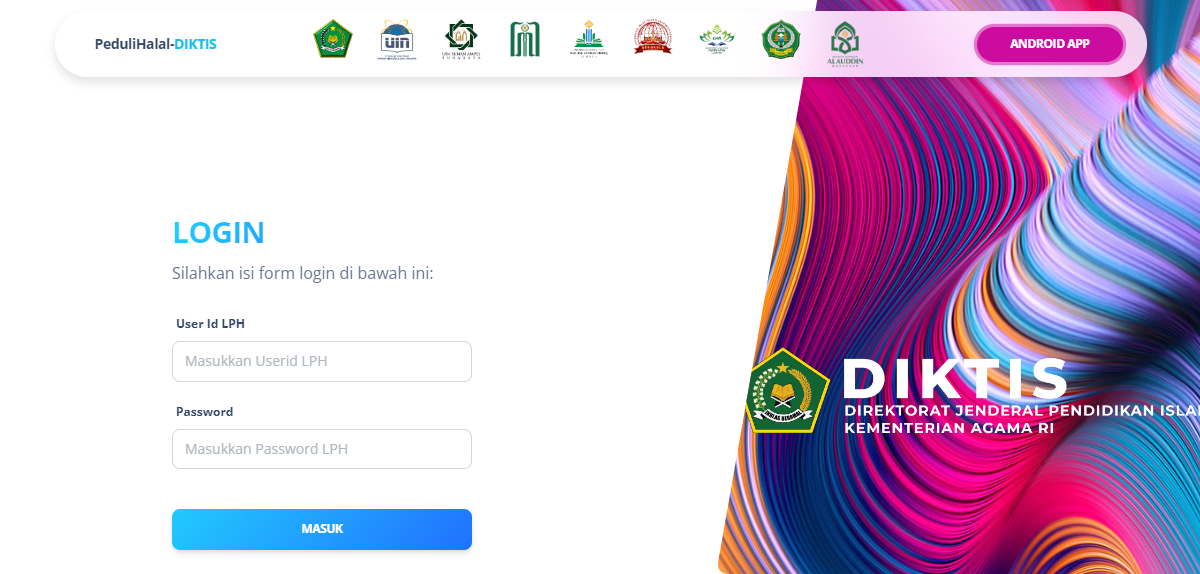KUALITAS LULUSAN PERGURUAN TINGGI DAN AKSEPTABILITAS STAKEHOLDERS
By Mastuki HS.
Organization for Economic Co-operation Development (OECD) melaporkan, “Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah sarjana terbanyak kelima di dunia pada tahun 2020 mendatangâ€. Data ini merupakan proyeksi dari upaya Indonesia untuk meningkatkan jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya. Padahal di sisi lain, penyerapan lulusan sarjana di Indonesia tergolong lambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran sarjana pada Februari 2013 telah mencapai 360.000 orang, atau 5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang.
Lebih lanjut OECD menilai, lulusan perguruan tinggi Indonesia gagal mengimbangi keinginan pasar. Banyak perusahaan sulit menemukan orang yang bisa berpikir kritis dan mampu membuat transisi yang mulus dalam bekerja. Hal ini ditengarai karena lulusan perguruan tinggi biasanya tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup. Kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja itulah yang kemudian menyebabkan penyerapan lulusan sarjana di dunia kerja mengalami pelambatan.
Mencermati laporan OECD tersebut, bukan lantas kita mengerutkan kening atau berkeluh kesah apalagi menyalahkan pihak-pihak lain. Justru laporan tersebut perlu menjadi warning bagi pengelola dan penyelenggara perguruan tinggi agar lebih awas dan tanggap terhadap perubahan dan perkembangan kebutuhan dunia kerja yang sangat dinamis. Karena bagaimanapun, perguruan tinggi masih dihargai sebagai salah satu pilar penting pembangunan bangsa. Perguruan tinggi diyakini bisa melahirkan generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, wawasan, ketrampilan, skills, dan kepribadian yang dibutuhkan bagi pembangunan bangsa. Keyakinan semacam itu mengharuskan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan bangsa, bertanggung-jawab, bermutu, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu melahirkan lulusan yang kompeten di bidangnya masing-masing.
Arus perubahan sosial yang selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan responsif (responsive capability) terhadap fenomena sosial yang berkembang di sekitarnya. Apalagi menghadapi perkembangan era kompetisi seperti sekarang ini, diperlukan kekuatan daya saing yang tangguh, dimana sumber daya insani atau human capital merupakan kuncinya.
Persaingan dalam penyediaan jasa pendidikan tinggi menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan perubahan internal perguruan tinggi jika ingin tetap eksis dan diminati masyarakat. Salah satu challenge itu misalnya diversifikasi bidang pekerjaan yang menuntut kompetensi dan keahlian spesifik. Kondisi ini mengakibatkan persaingan yang sangat ketat akan dialami para lulusan di dalam dunia kerja. Seperti disinggung pada laporan OECD di atas, masih ada masalah ketidaksinkronan antara keahlian yang diperlukan berbagai lapangan kerja dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi. Kualitas lulusan dihadapkan pada akseptabilitas pengguna (users/stakeholders).
Dampak lainnya adalah pada perubahan persyaratan yang juga sangat ketat di bursa kerja. Persyaratan kerja saat ini tidak hanya menekankan kualitas lulusan pada penguasaan hard skills (kemampuan teknis dan akademis), tetapi juga soft skills berupa kemampuan intra dan interpersonal seperti kemampuan beradaptasi, komunikasi, kepemimpinan, inisiatif, kemauan dan motivasi yang tinggi, komitmen, pengambilan keputusan, optimisme menghadapi hidup, pemecahan masalah, integritas diri (personal habits), keramahan (friendliness, hospitality, sociability), dan sebagainya. Dan ternyata modal sukses di lapangan pekerjaan, kompetensi akademik (teknis, hard skills) hanya menyumbang 20%, sementara kompetensi non akademik (soft skills) menentukan hingga 80% (wordpress.com).
Sebagai ilustrasi kenyataan masih rendahnya kualitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu misalnya pengakuan Lina Marianti, pencari eksekutif (headhunter) di JAC Recruitment, Jakarta. Menurut dia, perusahaan asing menolak lebih dari setengah lulusan universitas yang dia rekomendasikan untuk dipekerjakan. “Kami merekomendasikan lulusan-lulusan terbaik, tetapi yang terbaik itu pun tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan perusahaan,†kata Lina. "Mereka (pemberi kerja) mengeluh, lulusan universitas lokal tidak mampu mengaplikasikan teori ke dalam praktik. Mereka lemah dalam ketrampilan kepemimpinan dan analitis. Mereka buruk dalam bahasa Inggris dan pengetahuan produk,†tuturnya (www.esq-news.com).
Gambaran tersebut menyiratkan banyak hal. Pertama, kualitas lulusan. Kedua, penerimaan pasar pengguna. Dan ketiga, kesiapan perguruan tinggi menghadapi perubahan. Penyediaan lulusan yang berkualitas mengisyaratkan bukan saja pengetahuan, tetapi juga keahlian/kecakapan spesifik yang dibutuhkan pasar pengguna. Sebab jika tidak, seperti pernah disinyalir oleh Wakil Presiden, Prof Boediono, “perguruan tinggi yang tidak menjaga kualitas, ibarat pengedar uang palsu yang bisa merusak sistem berkepanjangan†(www.beritasatu.com).
Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi nasional, tidak akan luput dari challenge seperti itu. Kenapa? Karena selama ini ada kesan bahwa perguruan tinggi agama Islam (PTAI) hanya berkutat pada bidang-bidang yang berorientasi ‘akhirat’, bukan dunia. Program kajian dan ilmu-ilmu yang dikembangkan di PTAI lebih banyak bersentuhan dengan dunia spiritual dan adi-kodrati, tidak banyak bersentuhan dengan dunia industri, perusahaan, atau lapangan kerja yang kompetitif. Pasar pengguna lulusan PTAI selama ini terbatas pada pasar konvensional yaitu lingkungan Kementerian Agama dan institusi-institusi keagamaan (ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, lembaga dakwah, masjid, pesantren, dll). Bidang kerja mereka pun tidak jauh dari kebutuhan tenaga/profesi lembaga dan birokrasi Kementerian Agama.
Pandangan ini tidak salah. Meskipun sebenarnya dalam satu dasawarsa terakhir ini ada perubahan di PTAI berkenaan dengan ‘perluasan pasar pengguna’ atau pasar inkonvensional. Lulusan PTAI tidak hanya bekerja di bidang-bidang konvensional, tetapi juga inkonvensional seperti menjadi wartawan/penulis atau presenter di berbagai media massa, pejabat di birokrasi non keagamaan (Pemda, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hankam, Kepolisian, Polri/TNI), partai politik (PDIP, Golkar, PPP, PAN, PKB, Demokrat, dll), dan aktivis LSM. Diversifikasi perjalanan karir lulusan IAIN melalui pasar inkonvensional tersebut di satu sisi menggembirakan karena berkaitan dengan akseptabilitas pengguna, tetapi sisi lain merupakan problem bagaimana kualitas lulusan tersebut. Situasi ini menjadi bukti bahwa ada kesenjangan antara produk perguruan tinggi dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini merupakan tantangan umum yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia yang sedang bergerak menjadi negara maju. Dalam bahasa ilmiah, situasi ini disebut dengan unintended consequences, yakni ketidaksesuaian antara ilmu yang dipelajari pada saat kuliah dengan bidang kerja yang digeluti.
Jakarta, 2 Desember 2013