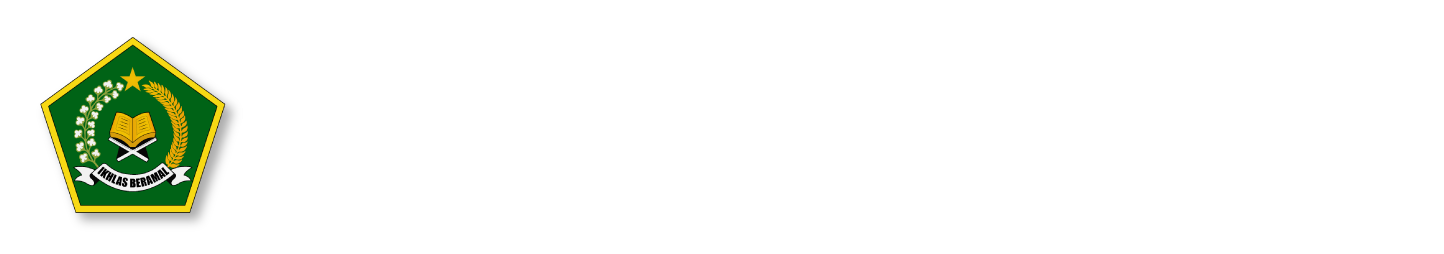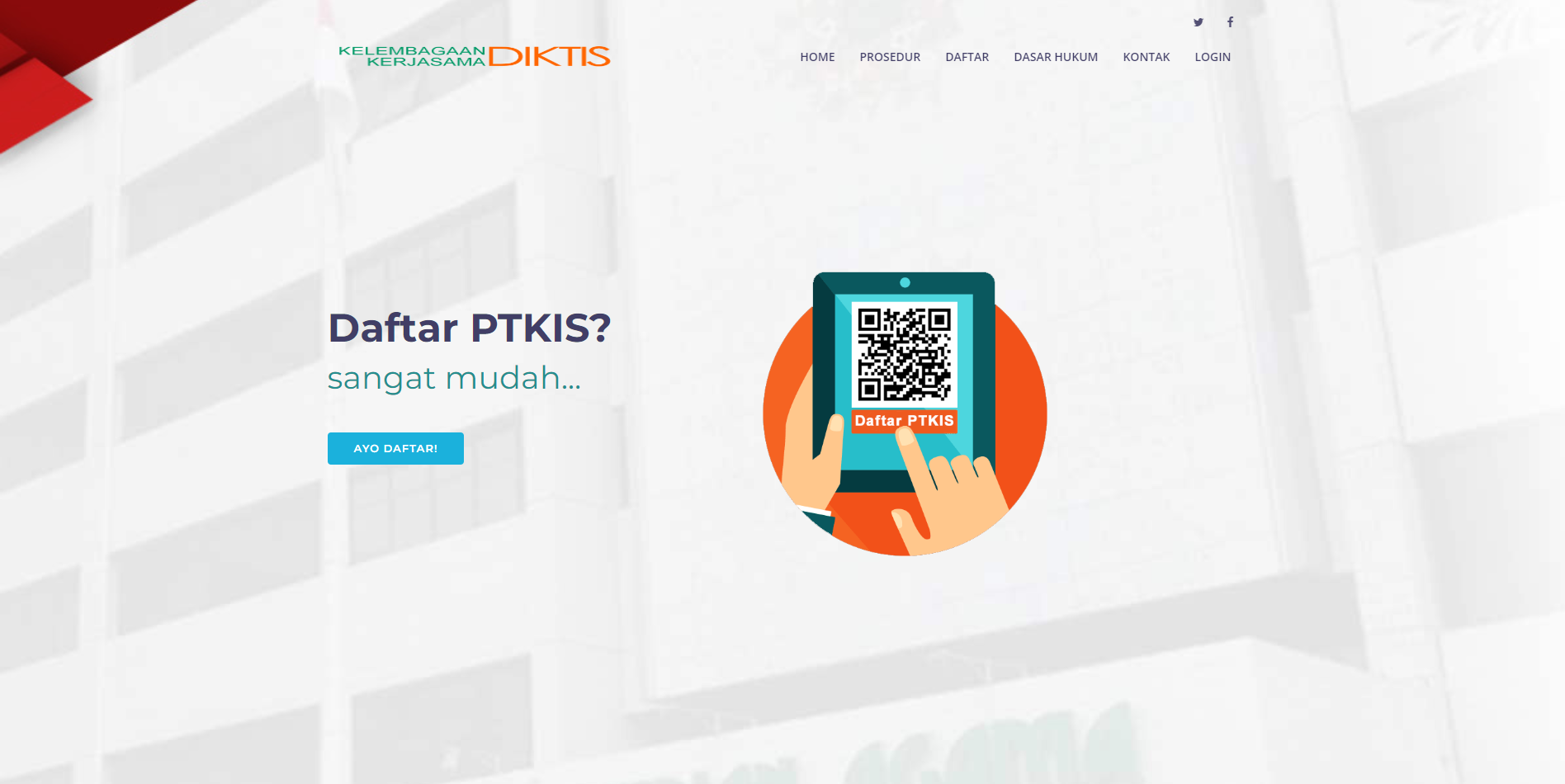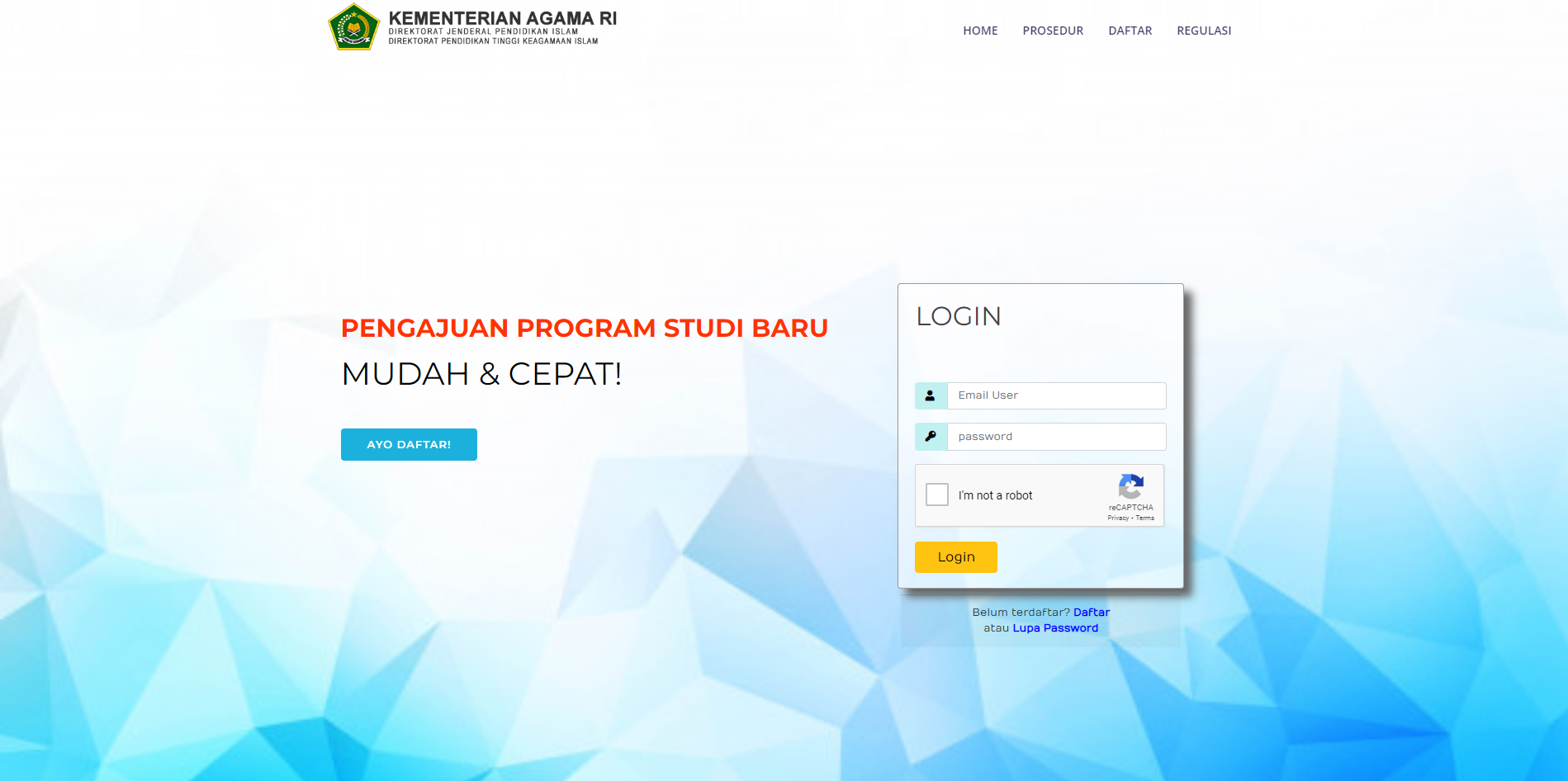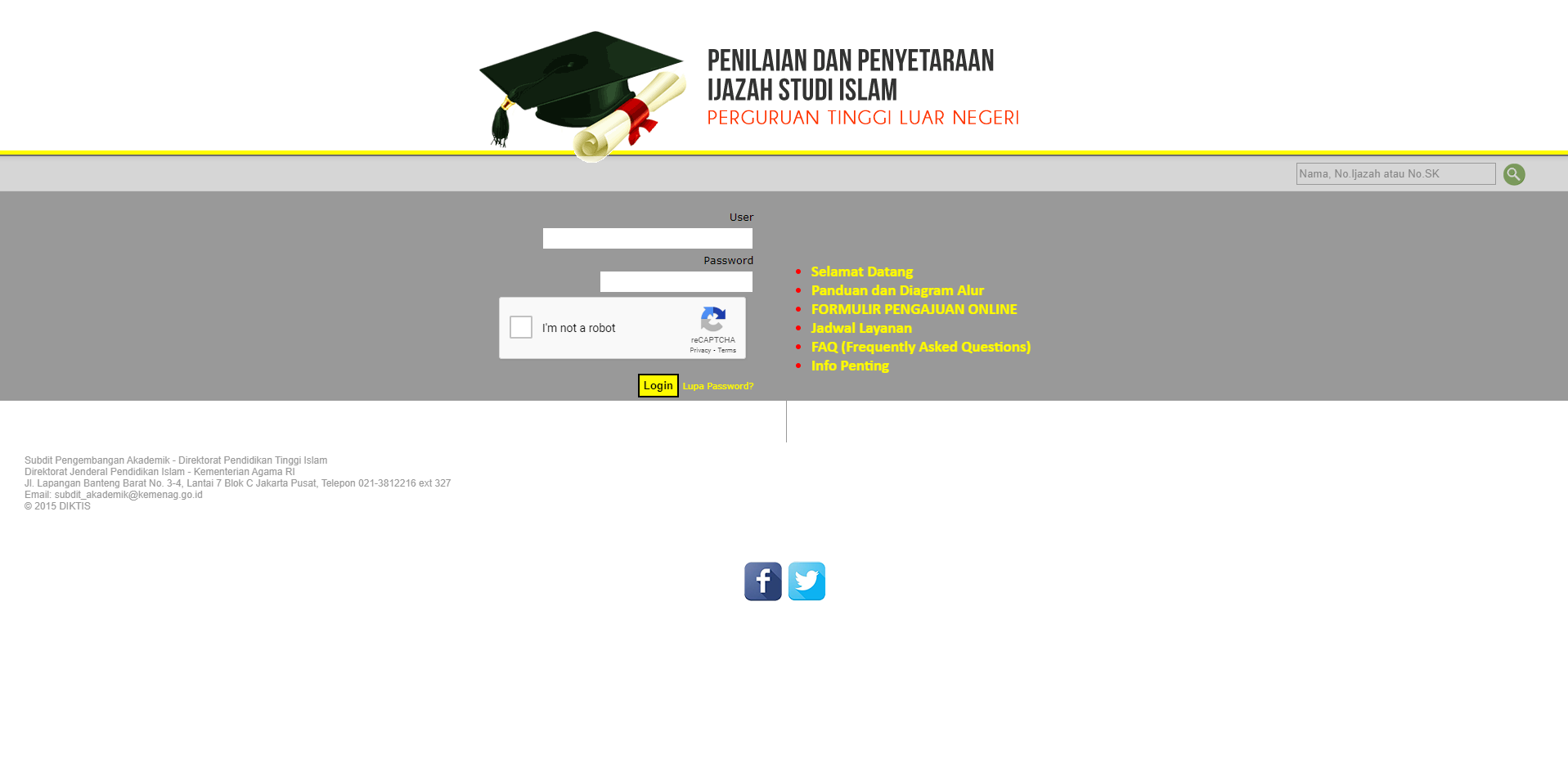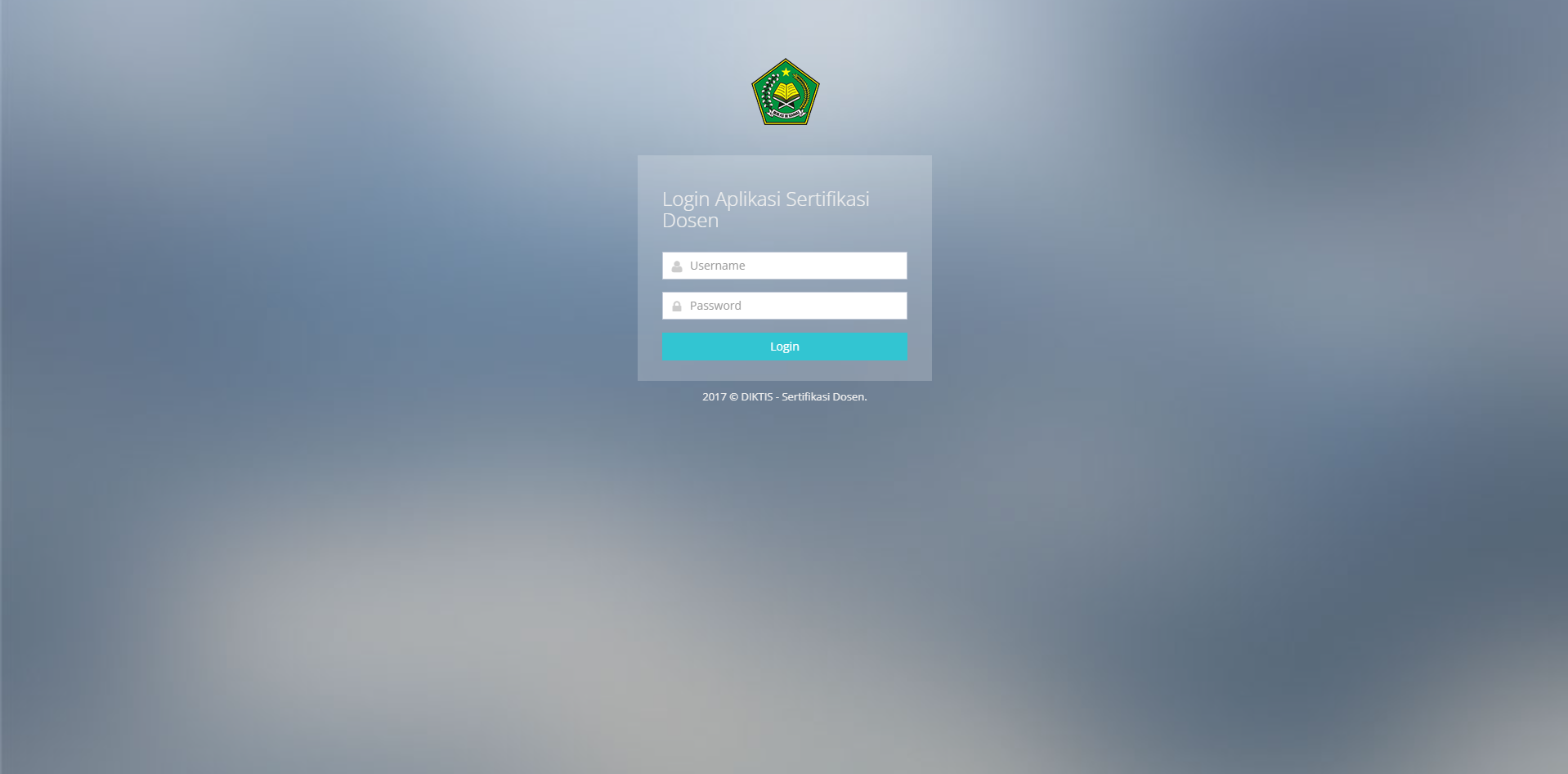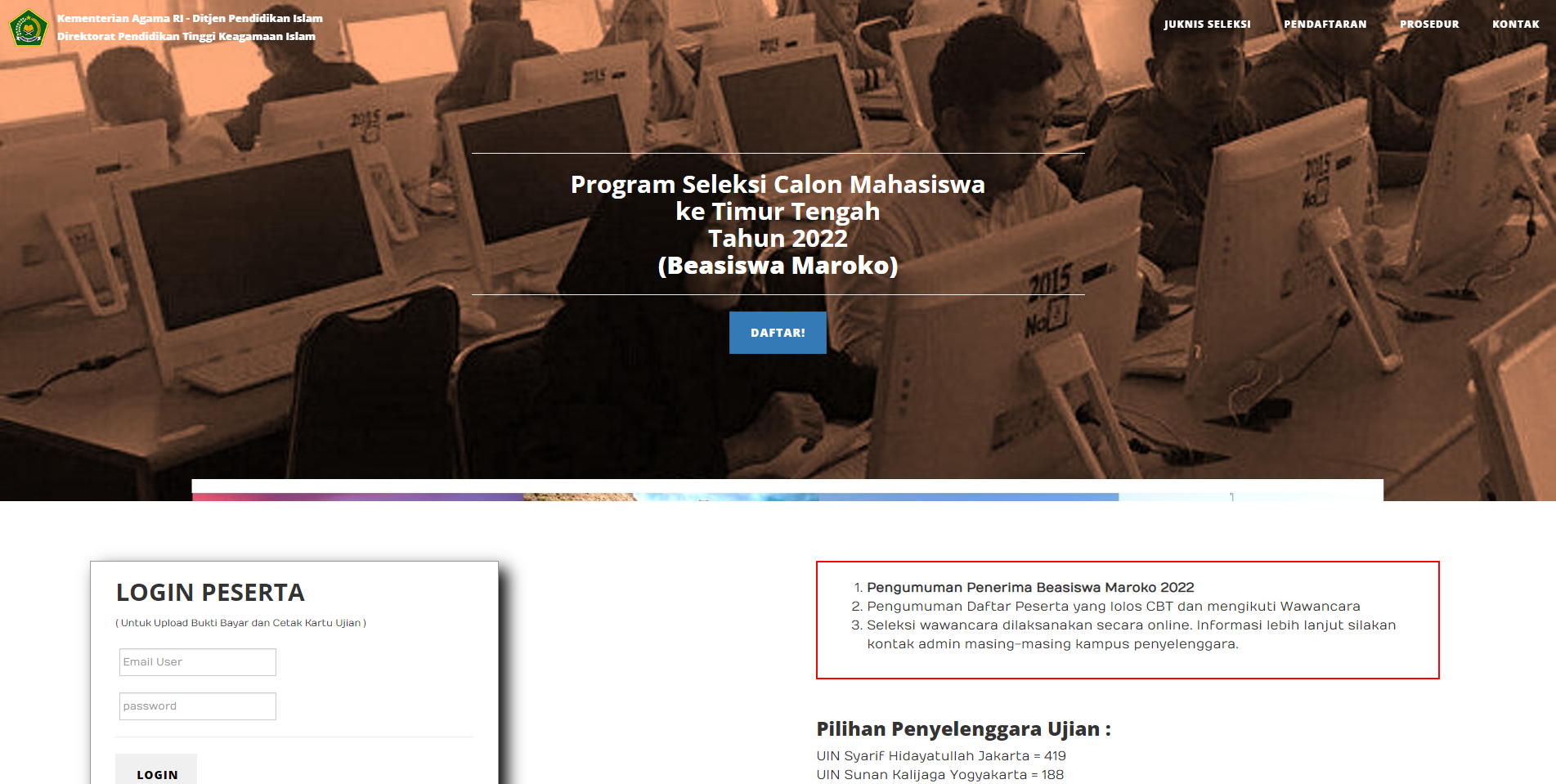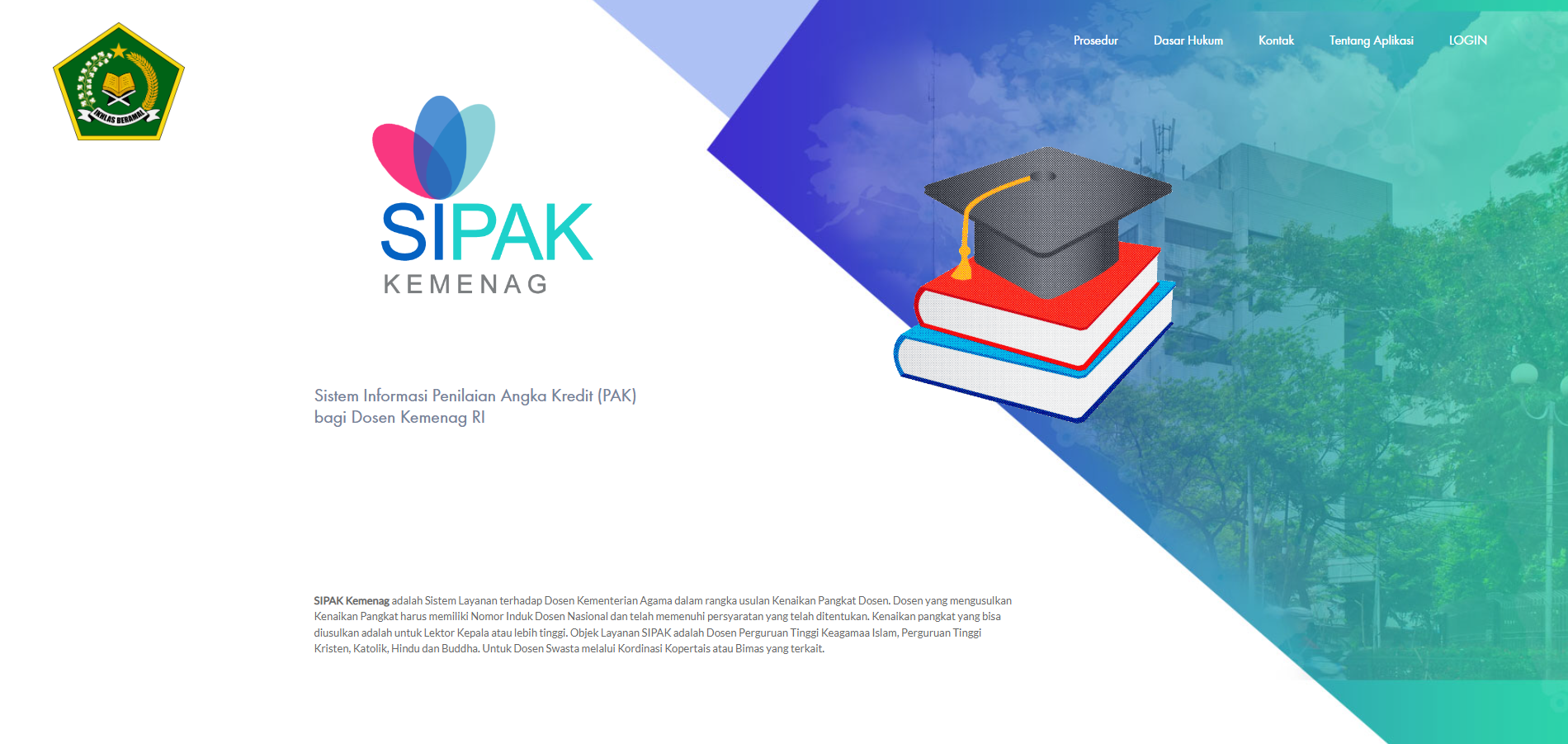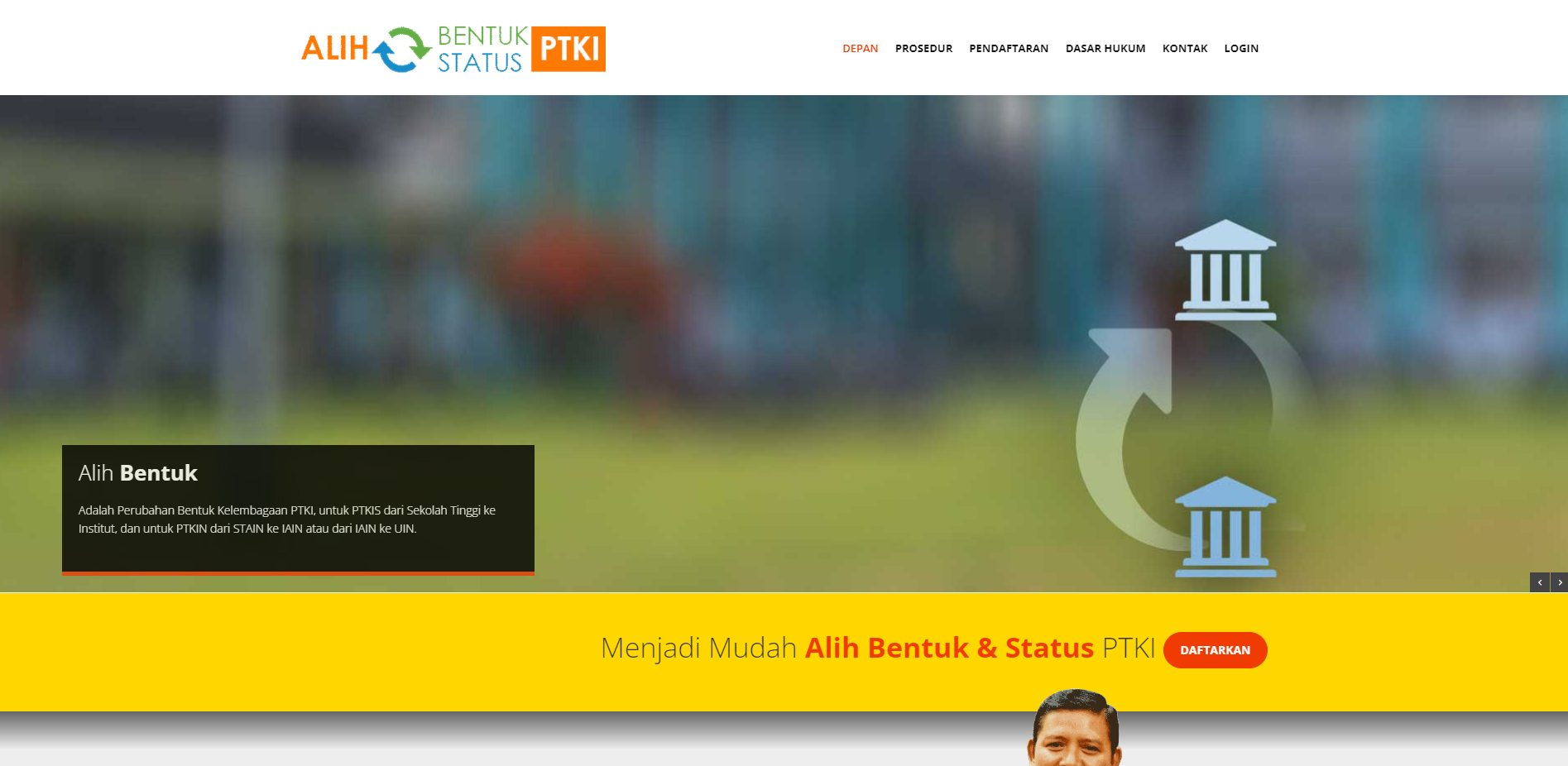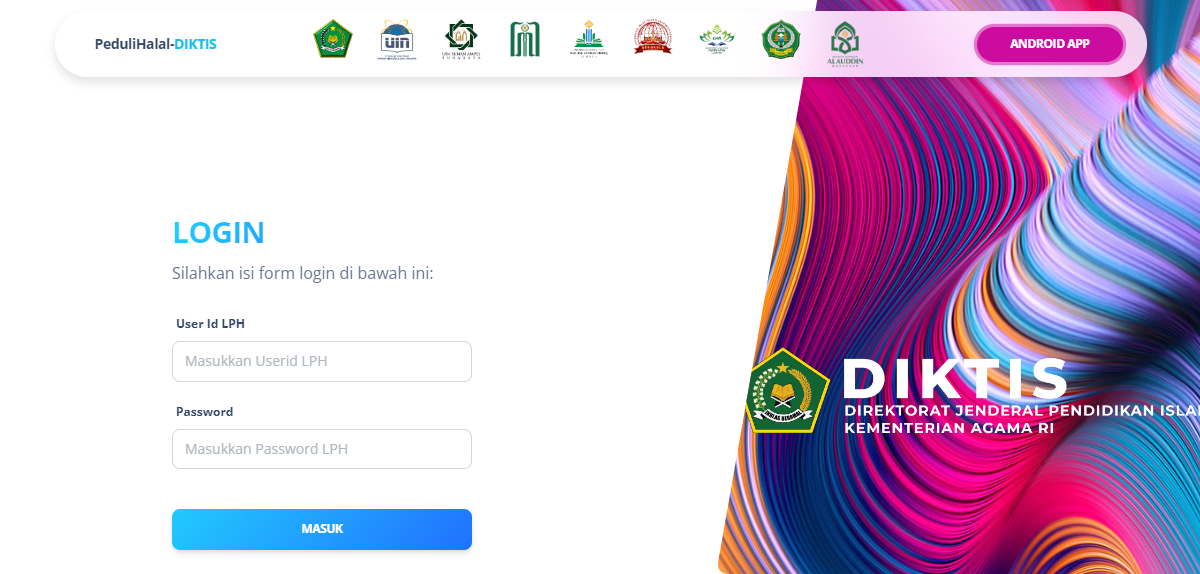MENEGUHKAN UIN/IAIN MENJADI JENDELA ISLAM INDONESIA
By Mastuki HS*)
Pada 1 Juli 2014 lalu, Badan Litbang Kementerian Agama menyelenggarakan diskusi menghadirkan Prof. Ronald Lukens-Bull, antropolog asal University of North Florida Amerika. Bicara tentang "Pendidikan Tinggi Islam Indonesia di Persimpangan Jalan", Profesor Ronald mendeskripsikan beberapa hal penting tentang dinamika dan gejolak pemikiran Islam yang terjadi pada pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Profesor Ronald melakukan penelitiannya di beberapa UIN dan IAIN. Meskipun tujuan penelitiannya, yang sudah menjadi buku dengan judul "Islamic Higher Education on the Cross Road", untuk konsumsi masyarakat Amerika Utara, temuan-temuannya menarik dicermati dan didiskusikan lebih lanjut.
Sebagai antropolog, Prof. Ronald mengendus adanya "battle ground" yang tampak dan tak-tampak dan hidup di PTAI menyangkut beberapa isu penting seperti wacana jender di PTAIN, tradisionalis vs modernis (variasi faham dan perdebatan keagamaan), transformasi atau perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN, dan perdebatan dinamik akibat varian kiblat keilmuan yang terjadi di PTAIN, antara alumni Timur Tengah (Saudi, Mesir, Yaman, dll) di satu sisi dan alumni universitas Barat (Amerika, Eropa, dan beberapa menyangkut Australia) di sisi lain. Dinamika terakhir ini merupakan imbas langsung dari pengiriman dosen yang berlangsung intensif sejak 1980-an pada masa Menteri Agama Munawir Sadzali baik ke universitas Barat maupun Timur Tengah.
Pendekatan antropologis yang dilakukan Prof. Ronald terhadap pendidikan tinggi Islam menarik diikuti karena bicara fenomena yang"nyata" di permukaan untuk memotret sesuatu "yang tak nyata" dan berkembang di area lebih luas, dalam konteks dinamika Islam Indonesia. Artinya, membahas lembaga pendidikan tinggi Islam semacam IAIN dan UIN dijadikan sebagai entry point untuk mengenal lebih dalam "apa yang terjadi dan sedang bergolak" di pedalaman (umat/komunitas) Islam Indonesia. Tatkala wacana, perdebatan, struggle, dinamika, dan fenomena itu dapat diungkap ke permukaan, akan dapat diketahui wilayah "gunung es" yang meluas di bawah permukaan. Gambaran kecil di IAIN/UIN menjadi cermin bagaimana wajah Islam Indonesia.
Isu yang berkembang selama ini di IAIN/UIN/STAIN yang menunjukkan rivalitas dan persinggungan antara kelompok tradisionalis versus modernis berikut dengan segala wacana dan praktik keagamaan yang khas dan berbeda (titik tengkar) hingga pada ranah titik singgung kedua kelompok muslim ini sejatinya representasi dari pergulatan serupa yang lama di kalangan dan merupakan wajah muslim Indonesia. Ditarik secara garis lurus atau bengkok sekalipun, rivalitas kelompok tradisionalis (kebanyakan di IAIN/UIN/STAIN diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan ’anak sejarahnya’: PMII, IPNU) dan modernis (biasanya Muhammadiyah beserta underbouw-nya: HMI, IMM atau PII) itu menjadi medan perluasan dari apa yang terjadi di masyarakat muslim Indonesia. Di sini Profesor Ronald berhasil mengungkap lebih jelas apa yang sedang terjadi itu dimulai dari ’mengintip’ wilayah mikro di tingkat IAIN/UIN lalu menariknya ke wilayah makro Islam Indonesia.
Pendekatan yang sama dilakukan Prof. Ronald saat mencandera orientasi keilmuan yang berkembang di IAIN/UIN. Tatkala IAIN berdiri tahun 1960 di Yogyakarta dan Jakarta, orientasi keilmuan yang berkembang di lembaga milik umat Islam ini bersifat tunggal mengacu pada kajian Islam (dirasat islamiyah) seperti terjadi di Universitas Al-Azhar Mesir. Selain pembidangan program kajian Islam yang ketat pada ilmu-ilmu keislaman ’tradisional’: Al-Qur’an, hadis, ushul fiqh, fiqh/syariah, dan bahasa Arab, penamaan fakultas di IAIN persis mengikuti Al-Azhar yakni fakultas ushuluddin, adab, syariah, tarbiyah, dan dakwah.
Kajian Islam didefinisikan sebagai kepatuhan dan kelanjutan kajian yang dirintis oleh para ulama zaman pertengahan Islam, dan itu hanya pada ilmu-ilmu Islam seperti disebut dimuka. Karena itu, kajian Islam yang berlangsung di IAIN bersifat konservatif (mewarisi dan mentransfer ilmu-ilmu Islam kepada mahasiswa) tanpa ada kritik, tetapi lebih bersifat ’menerima’, bersifat ideologis, dogmatis, historis, dan merupakan dakwah islamiyah. Kajian Islam di IAIN dianggap sebagai kelanjutan dari kajian Islam di pesantren atau madrasah yang juga bersifat dogmatis. Dosen yang mengajar di IAIN berlatarbelakang lebih homogen: dari atau mendapat pendidikan pesantren, alumni universitas Al-Azhar, atau jebolan pendidikan tradisional di Haramain (Makkah dan Madinah).
Pelan namun pasti, perubahan orientasi keilmuan di IAIN terjadi dari dalam sendiri. Kepulangan sejumlah sarjana dari universitas Barat (terutama McGill Kanada) ke IAIN pada awal 1980-an membawa angin perubahan. Untuk pertama kali --ini kejutan pertama-- sarjana Muslim belajar Islam dari Barat, bukan pesantren atau Al-Azhar. Barat yang diidentifikasi sekuler dan rasionalis masih lekat pada ingatan kalangan Muslim secara umum. Bahwa Islam itu lahir dari Makkah, karenanya gudang ilmu-ilmu keislaman hanya ada di Makkah dan sekitarnya di kawasan Timur Tengah. Kenapa belajar Islam dari mereka? Inilah kira-kira kecurigaan terhadap sarjana yang kembali dari Barat.
Alumni Barat era awal itu adalah Mukti Ali, Harun Nasution, Anton Timur Djaelani, Muljanto Sumardi dan lain-lain, menyebut beberapa di antara mereka. Mukti Ali kembali ke Indonesia, kemudian beraktivitas di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sementara Harun Nasution di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Anton Timur dan Muljanto menjadi birokrat di Kementerian Agama. Dari tangan mereka inilah reformasi dan reorientasi kajian Islam di IAIN mulai. Kecurigaan ’kalangan tua’ benar adanya. Mukti Ali memperkenalkan mata kuliah perbandingan agama yang menjadi titik awal pengenalan kajian Islam lebih kritis. Harun Nasution lebih-lebih mengintrodusir kajian Islam yang kontroversial seperti filsafat, kalam/teologi, tasawuf, dan pemikiran modern dalam Islam. Bukan sebab mata kuliahnya, tetapi pendekatan rasional dan kritis terhadap Islam yang menjadi titik picu perdebatan di internal IAIN. Identifikasi Harun pada pemikiran Muktazilah menjadi penyulut api ’permusuhan’ kalangan muda dengan kalangan tua --mengikuti istilah pembaharuan di Minangkabau yang terjadi seabad sebelumnya.
Api permusuhan antara kalangan tua dan pembaharu IAIN yang diwakili alumni Barat ini hanyalah permukaan dari ’gunung es’ yang disebut Profesor Ronald. Perdebatan sesungguhnya lebih seru dari itu. Saat Mukti Ali menjadi Menteri Agama dan Harun Nasution menjadi Rektor IAIN Jakarta, kalangan tua merasa saat itulah alih generasi dan ’alih kekuasaan’ mulai terjadi. Selama bertahun-tahun Kementerian Agama dipegang oleh kalangan tradisionalis yang digenggam NU. Kiai Wahid Hasyim, Kiai Masjkur, dan Kiai Saifuddin Zuhri --ayah kandung Menteri Agama saat ini, Lukman Hakim Saifuddin-- adalah representasi kalangan tradisionalis yang berhasil mengembangkan Kementerian Agama dan IAIN dengan karakteristik kajian Islam khas kalangan ini. Sekarang dua lembaga besar umat Islam itu beralih ke kalangan modernis (Mukti dan Harun dianggap sebagai anak muda yang lahir dari rahim kalangan modernis) tentu bukan sekedar ketidakrelaan ’ladangnya direbut orang lain’, tapi menyangkut keberlanjutan cita-cita Islam, alih generasi, perubahan orientasi politik, kehilangan cantholan ideologis, dan menyempitnya ruang sosial-budaya-politik yang berdampak luas pada kalangan tradisionalis.
Model kajian Islam yang kritis, rasional, bebas, dan historis (jangan samakan dengan liberal) itu bekasnya hingga kini dapat ditemui di hampir semua perguruan tinggi Islam, baik berbentuk STAIN, IAIN (di dalamnya juga swasta), maupun UIN. Kawan-kawan ada yang menyebut "Harunisme" untuk menyebut pengaruh pemikiran Harun Nasution karena banyak magister dan doktor di perguruan tinggi Islam adalah murid langsung pak Harun yang merupakan jebolan Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat terakhir pengabdian Pak Harun. Diakui atau tidak modernisasi kelembagaan dan pemikiran yang terjadi di IAIN saat itu membuahkan hasil manis berupa kebebasan akademik dan mimbar akademik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi dan untuk IAIN. Prof Ronald menyebut gambaran kecil misalnya, mengapa mahasiswa Malaysia tertarik kuliah di IAIN Sumatera Utara Medan yang sederhana (untuk tidak menyebut kampusnya jelek) karena ada kebebasan dalam kajian di IAIN yang lebih bebas dan kiritis. Islam menampakkan ada banyak warna di Indonesia, dan itu bisa ditemui di IAIN; --sesuatu yang sulit ditemui di Malaysia. Dengan gambaran kecil itu, kita bisa mengungkap potret yang lebih besar tentang geliat pemikiran Islam Indonesia.
Menyangkut perubahan atau transformasi kelembagaan IAIN/STAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), Profesor Ronald menengarai adanya perubahan orientasi keilmuan yang mengarah pada penyatuan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum yang sebelumnya dalam praktek pendidikan tinggi Islam terpisah dan cenderung dikotomik. Dalam perspektif perbandingan dengan apa yang terjadi pada masyarakat Amerika, yang menjadi concern penelitian Profesor Ronald, perubahan bentuk pendidikan tinggi keagamaan yang mengadopsi ilmu-ilmu ’sekuler’ adalah kasus yang menarik perhatian. Sayangnya Profesor Ronald kerap menggeneralisir proses yang saya sebut "penyesuaian" keilmuan itu semata dari dan untuk perspektif orang Amerika. Bukan hal yang salah karena tujuan penelitiannya memang untuk konsumsi masyarakat Amerika. Tetapi pada saat buku hasil penelitian ini dipublikasikan untuk khalayak Muslim Indonesia, beberapa istilah dan penyebutan nomenklatur ilmu atau penggambaran "yang tampak" itu tidak relevan, tidak available, dan kadang tidak mewakili apa yang terjadi pada ’pedalaman’ internal IAIN/UIN maupun tokoh pengusung transformasi tersebut. Dengan kata lain, apa yang ingin diungkap dari "gunung es" perdebatan transformasi kelembagaan UIN tidak terepresentasi dengan baik sesuai dengan apa adanya.
Sesungguhnya perdebatan dan proses transformasi kelembagaan UIN yang diusung oleh banyak tokoh IAIN itu tidak terjadi tiba-tiba. Sejak Harun Nasution menjabat Rektor IAIN Jakarta, kemudian dilanjutkan oleh Quraish Shihab, ide transformasi dan perubahan IAIN menjadi UIN itu sudah ada. Inisiatif ini kemudian mendapat mementum kuat di berbagai PTAI, terutama IAIN Jakarta, IAIN Yogya, dan STAIN Malang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bersatu menggolkan transformasi ke UIN tersebut. Tokoh dan “pelaku†di balik ide besar itu orang semacam Prof Azyumardi Azra MA, Prof Amin Abdullah MA, dan Prof. Imam Suprayogo --masing-masing mewakili lembaganya—yang kemudian merealisasikan ide itu menjadi kenyataan. Kabarnya mereka mengadakan serangkaian pertemuan intensif untuk memperoleh dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pendidikan, Bappenas, DPR/MPR, tokoh nasional hingga Presiden. Jika kemudian lahir UIN adalah hasil perjuangan banyak orang, banyak pemikiran, dan banyak tenaga yang dicurahkan.
Saya menyebut perubahan kelembagaan IAIN/STAIN menjadi UIN itu sebagai lompatan quantum dan mewakili reformasi pemikiran Islam Indonesia. Ia sebagai kelanjutan dari campuran antara keinginan, cita-cita, struggle, kecemasan, kegelisahan, dan optimisme dari tokoh-tokoh Islam (mewakili masyarakat Muslim dan puak cendekiawan Muslim) yang menginginkan lahirnya pendidikan tinggi Islam yang berwibawa di Indonesia. Makna universitas menunjuk dengan jelas adanya keinginan bahwa Islam dan pemikiran Islam tidak terbonsai hanya dan pada kajian Islam yang sempit (seperti di IAIN), tetapi meliputi semua bidang keilmuan. Dengan begitu Universitas Islam yang akan dilahirkan adalah lembaga yang mengkaji semua ilmu itu secara menyatu, terintegrasi (universum). Dan sesungguhnya secara historis, ide dan gagasan universalitas Islam dan penyatuan Agama dan Ilmu (umum, sekuler?) itu sudah pernah diwujudkan pemuka-pemuka Islam zaman 1950-an yang melahirkan Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta). Namun dalam perkembangannya kemudian terjadi pemisahan kembali dimana ilmu-ilmu agama Islam (yang dimaknai khusus dan sempit: syariah, dakwah, ushuludin, tarbiyah, dakwah) ’disapih’ menjadi IAIN, sementara fakultas umum UII yang membuka kajian ilmu-ilmu umum berdiri sendiri. Dalam kurun waktu lama penyapihan ini membelah pemikiran umat yang dikotomik dan parsial. Dan baru, setelah empat dasawarsa IAIN berdiri, di sela itu STAIN dikembangkan di berbagai daerah, UIN lahir di persis awal abad 21. Ini makna simbolik dimana UIN mewakili cita-cita yang dibayangkan (imagined, dreamed) para pemrakarsa akan terjadi sebagai titik tolak seperti masa keemasan Islam di zaman pertengahan dulu (golden age).
Secara antropologis, Prof. Ronald melihat adanya perbedaan pendapat tentang transformasi IAIN ke UIN itu tidak penting. Bahwa ada pihak yang mengklaim bahwa transformasi ke UIN itu merupakan upaya "mengembalikan kejayaan Islam seperti zaman keemasan di abad pertengahan", atau ada yang menyebut bagian dari integrasi agama dan ilmu. Apapun itu, tetapi kenyataannya transformasi IAIN ke UIN juga menyisakan perdebatan yang belum selesai di kalangan umat Islam Indonesia, dan di internal IAIN sendiri, sampai saat ini.
Saat IAIN/STAIN berniat menjadi UIN pada kurun 2002-2004 (kasus UIN Jakarta, Yogya, dan Malang), banyak pihak (internal IAIN maupun kalangan Muslim lainnya) yang tidak setuju, bahkan menentang. Perubahan IAIN ke UIN itu karena dikhawatirkan akan mengurangi (atau bahkan memerosotkan) kajian Islam yang sudah lama tertanam di IAIN. Ada yang menyebut marjinalisasi kajian Islam dan genderang kematian kajian Islam dikalahkan dengan ilmu-ilmu sekuler. Kekhawatiran itu juga masih berlangsung saat IAIN Sunan Ampel Surabaya akan menjadi UIN pada tahun 2011-2012. Sejumlah Kyai Jawa Timur menolak perubahan IAIN Surabaya menjadi UIN karena menurut mereka IAIN merupakan kelanjutan dari kajian Islam di pesantren. Ketika menjadi UIN akan ada masalah dalam hal kelanjutan kajian Islam yang tidak konek dengan pesantren. Meski akhirnya UIN Sunan Ampel berdiri di penghujung tahun 2013, secara antropologis tidak bisa dinafikan suara keberatan dari kalangan Muslim itu ada dan benar adanya. Sekali lagi, potret yang terjadi jelas, saat dan kala perubahan IAIN menjadi UIN adalah ’jendela’ untuk melihat geliat yang terjadi di dan dalam komunitas Islam Indonesia.
Sampai di sini, pelajaran yang bisa diambil dari kajian antropologis Prof Ronald dapat menjadi cara pandang lain dari dinamika yang terjadi di muara dan pedalaman perguruan tinggi Islam. Bahkan Prof Ronald menarik transformasi IAIN ke UIN itu ekuivalen dengan apa yang terjadi juga pada Seminari di Amerika yang beralih menjadi universitas. Ide, gagasan, perdebatan, dan perbedaan pendapat sampai implementasinya turut menyertai peristiwa itu. Saya kira pendekatan ini dapat membaca kasus-kasus lain di PTAI seperti jender, ilmu agama dan umum, dan lain-lain. [mas, 26/9/14]
*) Mastuki HS adalah Kepala Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Tulisan ini adalah hasil refleksi pribadi atas perkembangan kelembagaan PTKI mutakhir.